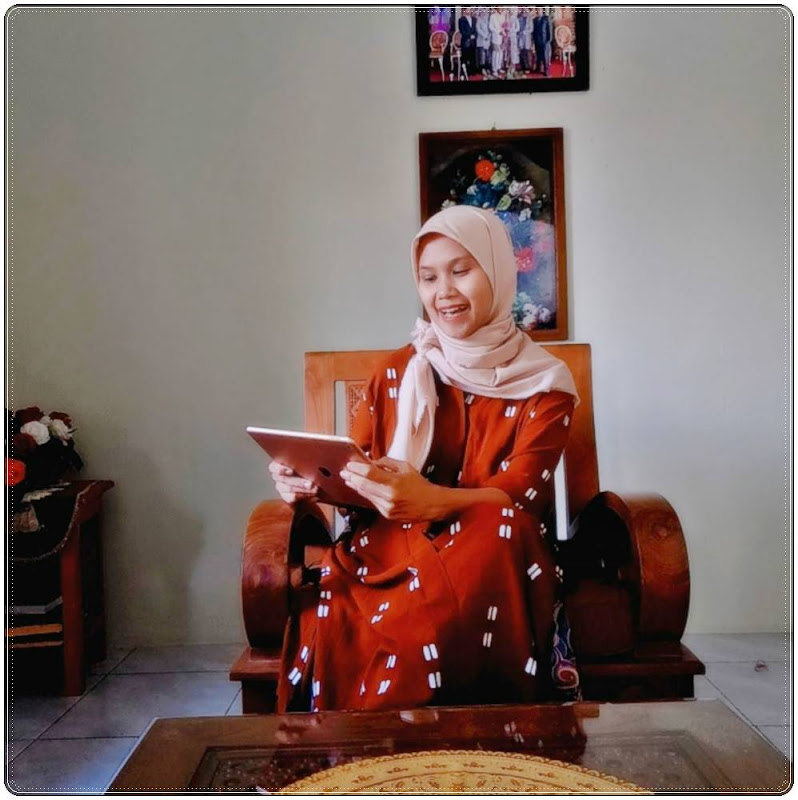Konflik Praktik Kegamaan “Shalat Jum’at” dan
Konvergensinya Di Kalangan Masyarakat Desa Nagarawangi
Oleh: Laelatul Badriyah
Latar Belakang
Dalam memahami agama di kalangan masyarakat luas, khususnya
memahami agama Islam, harus dibarengi dengan memahami budaya yang menyebar di
kalangan masyarakat. Karena tidak dapat dipungkiri, Islam masuk ke Indonesia
melalui budaya yang masyarakat miliki. Artinya budaya dijadikan alat untuk
masuknya Islam, sehingga Islam dapat diterima oleh kebanyakan masyarakat
Indonesia. Islam dapat diterima dengan
mudah karena memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan yang berlaku di
masyarakat. Sebaliknya Islam akan ditolak masyarakat apabila kebudayaan
masyarakat berbeda dengan ajaran agama.
Perbedaan budaya yang terjadi di setiap daerah di Indonesia
menjadikan pemahaman dan praktek
keagamaan yang berbeda-beda, sehingga kita akan sering mendengar istilah Islam lokal,
seperti Islam Aceh, Islam Padang, Islam Jawa, dan lain sebagainya. Dalam buku
Islam dan Budaya Lokal yang ditulis oleh Drs. Radjasa Mu’tashim, M.Si dikatakan
bahwa dua masyarakat yang berbeda kebudayaan akan berbeda pula dalam memahami
dan menjalankan agama yang dianutnya. Di sini dicontohkan bahwa Islam di
wilayah perkotaan (masyarakat industri) akan menampakkan wajah yang berbeda
dengan Islam di wilayah pedesaan (masyarakat tani), karena kebudayaan kota dan
desa berbeda. Contoh dari kebudayaan yang lain adalah perbedaan latar belakang
pendidikan di suatu masyarakat akan mempengaruhi pola pikir dan praktek
kegamaan. Seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Ciamis tepatnya di desa Nagarawangi,
telah terjadi perbedaan praktek keagamaan
dalam shalat Jum’at dan menimbulkan konflik berkepanjangan.
Dua kebudayaan yang berbeda, jika saling berinteraksi satu sama
lain akan menimbulkan konvergensi (penyatuan), dengan kata lain akan saling
melengkapi satu sama lain. Seperti disebutkan oleh Dr.H.M Bambang Pranowo dalam
sebuah artikel berjudul Agama dan Kebudayaan: Agama dalam Konteks Perubahan
Budaya, telah terjadi konvergensi antara Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU).
Dua organisasi besar Islam ini, sekarang mencoba untuk saling melengkapi satu
sama lain, tidak lagi fanatik pada beberapa paham yang dianuntnya, seperti
Muhammadiyah mulai membangun pesantren untuk generasi pemuda bangsa. Seperti
yang kita ketahui tradisi pesantren adalah tradisi NU. Begitu pun sebaliknya,
NU mulai membangun sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan yang modern. Tradisi
sekolah adalah tradisi Muhammadiyah dalam usahanya untuk mengejar segala
ketertinggalan masyarakat Islam pada jaman tekhnologi ini. Dua golongan besar
Islam ini, melihat bahwa mereka tidak akan lebih maju dari yang lain, jika
mereka hanya menggunakan tradisinya, sehingga mereka mencoba membuka diri, dan
saling melihat peluang untuk saling mengisi satu sama lain.
Di sini, penulis akan mencoba melihat sebuah kasus yang terjadi di
masyarakat desa Nagarawangi, dan melihat bagaimana konvergensi yang terjadi di
masyarakat desa ini. Penelitian kecil ini dinilai penting oleh penulis sebagai
usaha untuk memahami lebih dalam lagi tentang budaya, latar belakang sosial,
dan pendidikan berpengaruh pada praktik keagamaan. Juga untuk melihat kondisi
riil di masyarakat tentang pengaruh budaya terhadap praktik keagamaan.
Pendekatan kajian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang
difokuskan pada perolehan data deskriptif yaitu gambaran umum tentang desa
Nagarawangi, dan informasi tentang kasus yang telah terjadi di desa
Nagarawangi. Sumber data penting diperoleh dari pertama wawancara dengan tokoh
pemudi yang terlibat langsung dalam pemecahan masalah konflik ini, kedua
wawancara dengan seorang penghulu yang dinilai mengetahui asal-muasal kasus ini
terjadi. Serta studi kepustakaan dari buku yang berkaitan dengan Islam dan
Budaya, buku Fiqih Empat Mazhab sebagai data pendukung, dan memanfaatkan media
intenet.
Keadaan Desa Nagarawangi
Semula desa Nagarawangi bernama Nagarapageuh, tetapi karena pada
bulan Desember tahun 2012 kemarin telah melakukan pamekaran desa, sehingga
Nagarapageuh berubah menjadi Nagarawangi. Desa Nagarawangi terletak di
kecamatan Panawangan, kabupaten Ciamis, provinsi Jawa Barat.
Batas wilayah desa Nagarapageuh :
Sebelah Utara : Desa Nagarajati
Sebelah Selatan : Desa Jatinagara
Sebelah Timur : Desa Nagarajati
Sebelah Barat : Desa Situ Gede
Mata pencaharian warga desa Nagarawangi adalah bertani, berdagang,
beternak, berwirausaha ke daerah Jakarta dan menjadi Pegawai Negeri Sipil (3%),
Adapun latar belakang pendidikan warga desa Nagarawangi 70% lulusan SD dan 30%
lulusan SMA. Adapun generasi muda mulai memilki kesadaran untuk melanjutkan
sekolah ke jenjang sarjana.
Dari data yang didapatkan tentang latar belakang pendidikan dan mata
pencaharian masyarakat desa Nagarawangi menunjukan bahwa rendahnya minat untuk
belajar di sekolah formal, karena berbagai alasan, salah satu alasan yang
menonjol menurut penulis adalah faktor ekonomi yang cukup rendah. Kebanyakan
orang tua lebih memilih menikahkan anaknya atau bekerja (merantau) setelah
lulus sekolah di SMP atau SMA daripada untuk melanjutkan sekolah ke jenjang
lebih tinggi, mengingat biaya pendidikan yang mahal di negara kita. Hal ini
membuat wawasan tentang ilmu pengetahuan mereka terabatas dan cenderung
berpikir tertutup. Kebanyakan orang hanya menjadi pengikut yang tanpa tahu
alasan dan maksudnya atau dalam istilah Islam biasa disebut taklid buta.
Seperti kasus yang terjadi di desa ini. Kasus tentang pelaksanaan shalat Jum’at
menggunakan shalat dzuhur dan tidak menggunakan shalat dzuhur. Hal ini
menimbulkan konflik berkepanjangan sampai kurang lebih memakan waktu lima belas
tahun.
Hasil Penelitian
Menurut dua sumber yang telah penulis wawancarai (Nia Agustina/S1/Guru),
dan (Sutardi/Penghulu) konflik ini sudah berlangsung kurang lebih 15 tahun.
Mencuatnya konflik ini ke permukaan masyarakat sekitar tahun 1998, dan baru
dapat diselesaikan satu tahun yang lalu, tepatnya tahun 2012. Konflik ini
terjadi karena perbedaan pendapat antara dua tokoh agama di desa Nagarawangi.
Tokoh agama A[1]
yang dikenal oleh masyarakat berlatar belakang pendidikan pesantren tradisional
berpendapat bahwa setelah ibadah shalat Jum’at harus tetap melaksanakan shalat
dhuhur empat rakaat dengan alasan sebagai kehati-hatian, tokoh agama ini
khawatir jika shalat Jum’at yang telah dilakukan tidak sah. Sedangkan tokoh
agama B yang dikenal oleh masyarakat berlatar belakang pendidikan pesantren Modern
Darussalam di jantung kota Ciamis ini berpendapat bahwa setelah ibadah shalat
Jum’at tidak harus melaksanakan shalat dhuhur, karena dua rakaat shalat Jum’at
telah mengganti empat rakaat shalat dhuhur. Dalil yang menerangkan hal ini
adalah "Apabila datang waktu siang
hari Jum'at maka shalatlah dua rakaat." (H.R. Dar Qutni). Seandainya
sholat dhuhur masih wajib, maka Rasulullah s.a.w. tentu tidak memerintahkan
hanya dua rakaat saja. Dua permasalahan ini menjadi pertentangan sengit di
antara dua tokoh agama, dan yang menjadi korban dari pertentangan ini adalah
masyarakat dan generasi pemuda. Dari perbedaan pendapat ini, tokoh agama A yang
mengikuti organisasi Islam NU menyangka bahwa tokoh agama B mengikuti
organisasi Islam Persis.
Setelah melakukan perbincangan
panjang yang tak kunjung menghasilkan benang merah, akhirnya tokoh agama B
membangun mesjid kembali di samping mesjid yang telah dibangun berpuluh-puluh
tahun yang lalu. Jarak antara dua mesjid tersebut kurang lebih seratus meter,
yang hanya terhalangi oleh kolam dan dua rumah warga sekitar. Hal ini
menjadikan adanya pelabelan mesjid. Mesjid pertama adalah mesjid yang digunakan
oleh tokoh agama A dan jamaahnya, begitupun dengan mesjid kedua digunakan oleh
tokoh agama B dan jamaahnya. Adapun menurut keterangan yang didapatkan, jumlah
jamaah shalat Jum’at di setiap masjid mencapai lebih dari empat puluh jamaah.
Ini berarti telah menggugurkan syarat sahnya shalat Jum’at menurut pendapat Imam
Syafi’I dan Imam Hambali. Selama konflik ini berlangsung tokoh agama A
memanggil ustadz dari desa lain untuk mengajarkan ilmu keagamaan di mesjid
pertama.
Konflik ini berdampak pada
pelaksanaan dua perayaan hari besar Islam: Idul Adha, dan Idul Fitri.
Pelaksanaan shalat Idul Adha dan Idul Fitri ini pun berlangsung di dua mesjid
itu, sesuai dengan kubu masing-masing. Jamaah untuk kedua kubu ini, cenderung
berimbang, karena hampir seluruh masyarakat di desa ini masih mempunyai
hubungan darah satu sama lain.
Konflik ini menimbulkan keresahan
dan kegelisahan di kalangan pemuda yang pendidikannya baik (lulusan S1), yang
kemudian pemuda-pemudi ini dapat menggerakkan pemuda-pemudi yang lain. Mereka
berinisiatif untuk mendamaikan dua tokoh agama ini, sehingga mereka mendirikan
Himpunan Pemuda-Pemudi Nagarawangi (HPPN) dengan bekerja sama bersama aparat
desa. Usaha mereka untuk mendamaikan dua tokoh agama ini adalah mengadakan
acara Halal bi Halal setiap tahun, tepatnya saat perayaan Idul Fitri. Isi acara
tersebut berupa ceramah dan pentas seni dari generasi muda. Pentas seni yang
diselenggarakan ini berisi drama, tari, hadlroh, kosidah, dan lain-lain. Adapun
usaha kepala desa adalah mengunjungi tokoh agama tersebut sekaligus melaksanakan
shalat Jum’at di dua mesjid secara bergantian setiap minggu. Tetapi usaha yang
dilakukan oleh kepala desa dan HPPN ini
tak kunjung mendapat respon dari kedua tokoh agama, mereka seperti abai
terhadap usaha yang dilakukan oleh generasi muda. Jalan lain yang diambil oleh
pemuda tersebut adalah demo. Akhirnya dengan aksi tersebut menghasilkan
perdamaian hitam di atas putih yang dibubuhi materai. Mereka bersalaman, dan
berdamai, walaupun pelaksanaan shalat Jum’at masih dilaksanakan di mesjid
masing-masing. Tetapi untuk dua perayaan hari besar Islam sudah dilaksanakan di
dalam satu mesjid (mesjid pertama).
Walaupun konflik ini terlihat sudah
selesai, tetapi sejatinya belum, pada pelaksanaan shalat Idul Fitri ini, kedua
tokoh agama tersebut kembali berselisih, mereka sama-sama ingin berkhutbah
dalam pelaksanaan shalat Idul Fitri. Dari sini, pertikaian kembali dimulai.
Mereka saling mempertahankan ego masing-masing.
Adapun kehidupan sosial masyarakat
setempat selama konflik ini berlangsung, mereka tetap saling berinteraksi satu
sama lain, menyatu, dan rukun, contohnya gotong royong dalam membantu persiapan
pelaksanaan pernikahan. Konflik akan muncul di masyarakat ketika dalam suatu
perkumpulan membahas tentang pelaksanaan shalat Jum’at. Masyarakat akan saling menyalahkan
satu sama lain. Padahal kebanyakan masyarakat dapat dikatakan hanya ikut-ikutan
saja (taklid buta), tanpa mengetahui dasar-dasar yang jelas.
Pada tahun 2012, saat usia tokoh
agama A sudah tidak lagi muda, ia mengalami gangguan kesehatan, hal ini
menimbulkan kesadaran pada diri tokoh Agama A untuk melakukan perdamaian yang
sesungguhnya. Tokoh agama A, meminta maaf pada tokoh agama B atas segala
kesalahan dan perselisihan yang terjadi sangat lama ini. Kedua tokoh agama
saling memaafkan dan menyadari kesalahan masing-masing. Ini sebagai awal
lahirnya perdamaian di desa ini. Kedua tokoh agama bersatu, masyarakat pun tak
lagi ikut-ikutan beselisih pendapat, dan mesjid yang kedua digunakan untuk
sekolah TPA (sekolah yang memperlajari tentang dasar-dasar agama untuk
anak-anak kecil). Pelaksanaan shalat Jum’at kembali dilaksanakan di satu
mesjid, begitu pun dengan dua perayaan hari besar Islam. Perbedaan menggunakan
shalat dhuhur atau tidak sudah tidak menjadi permasalahan, semuanya dilimpahkan
pada keyakinan masing-masing. Masyarakat yang masih melaksanakan shalat dhuhur
setelah shalat Jum’at diperkenankan untuk melaksanakannya secara munfarid.
Pendapat Ulama Tentang Shalat Jum’at[2]
Empat Imam mazhab sepakat bahwa apabila seseorang meninggalkan
shalat Jum’at, hendaknya ia shalat dzuhur. Apakah shalat dzuhur itu dikerjakan
secara berjama’ah atau sendiri-sendiri? Imam Hanafi dan Imam Maliki berpendapat
secara sendiri-sendiri. Imam Syafi’i dan Imam Hambali berpendapat secara
berjama’ah.
Menurut
pendapat Imam Syafi’i dan Imam Hambali shalat Jum’at sah kecuali dihadiri empat
puluh orang. Imam Hanafi berpendapat sah shalat Jum’at yang dihadiri empat
orang saja. Imam Maliki berpendapat
shalat Jum’at tetap sah, meskipun dihadiri kurang dari empat puluh
orang. Namun, tidak wajib mengerjakannya bagi orang bertiga atau berempat.
Apabila makmum masbuq mendapatkan satu rakaat bersama imam, maka ia
telah mendapatkan seluruh shalat Jum’at. Sedangkan jika kurang dari itu, maka
tidak dihukumi telah mendapat seluruh shalat Jum’at, dan ia harus shalat dhuhur
empat rakaat. Demikian pendapat Imam Maliki dan Imam Hambali.
Dari beberapa pendapat di atas menunjukan bahwa, shalat dhuhur
tetap ditunaikan saat hari Jum’at ketika ada beberapa kendala dalam
melaksanakan shalat Jum’at. Pertama karena seseorang meninggalkan shalat
Jum’at, kedua karena makmum masbuq (tertinggal dalam shalat berjama’ah Jum’at).
Dalam buku Fiqih Empat Mazhab ini, penulis tidak menemukan pendapat yang
mengharuskan melaksanakan shalat dhuhur setelah menunaikan shalat Jum’at tanpa uzur.
Kesimpulan
Dari konflik yang telah dipaparkan
di atas, penulis melihat bahwa konflik ini terjadi karena perbedaan latar
belakang pendidikan diantara dua tokoh agama tersebut, dan masyarakat yang
berlatar belakang pendidikan yang
rendah, menerima dengan tanpa menyaring dan mengikuti apa saja yang diajarkan
oleh dua tokoh agama tersebut. Jika kebanyakan masyarakat mempunyai latar
belakang pendidikan yang baik, mungkin saja konflik ini akan terselesaikan
lebih dini atau bahkan tidak terjadi sama sekali, karena adanya kontrol dari masyarakat.
Dalam konflik ini, penulis melihat ada dua
konvergensi yang terjadi. Pertama konvergensi langsung, kedua konvergensi tidak
langsung. Konvergensi langsung terlihat ketika dua tokoh agama saling menyadari
kesalahan masing-masing dan saling memaafkan. Dan hal ini menimbulkan penyatuan
secara general. Semua masyarakat bersatu seiring dengan bersatunya dua tokoh
agama yang menjadi panutan mereka. Mereka tidak lagi berselisih paham tentang
shalat Jum’at. Mereka hidup berdampingan secara damai.
Konvergensi tidak langsung terjadi
ketika masyarakat dapat bersatu dalam melaksanakan hubungan sosial seperti
gotong royong dalam membantu persiapan pelaksanaan pernikahan, dan acara-acara
yang lainnya saat konflik ini masih berlangsung.
Dalam kehidupan sosial seyogyanya kita selalu menghargai satu sama
lain dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, serta menerapkannya dalam
berbagai aspek sosial dan agama. Begitu pun kita harus tetap saling menghargai
tentang perbedaan praktik keagamaan yang beredar di masyarakat luas.